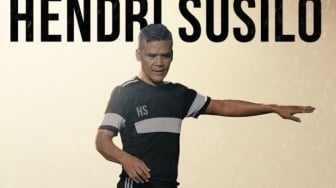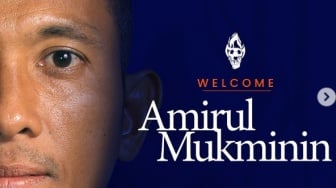Pep harus menyesuaikan jam latihannya dengan budaya jam karet. Lalu Pep harus membiarkan pemainnya diurut pasca cedera. Kemudian mengijinkan pemain ikut tarkam.
Puncaknya di lapangan, Pep harus relakan kipernya tendang bola jauh ke depan tanpa arah. Mana mungkin?
Jika hari ini Pep bekerja membangun sepakbola Indonesia. Apakah kita berani ikuti Pep? Atau kita masih menggerutu bilang ilmu Pep ketinggian dan tidak cocok dengan budaya Indonesia?
"Hidup itu memang pilihan. Celakanya, menjadi bodoh dengan menikmati kualitas sepakbola yang gini-gini saja juga sebuah pilihan. Selamat menjadi bodoh!," ucap Coach
Baca Juga:Achmad Yakub: Cegah Karhutlabun Butuh Kolaborasi Melibatkan Petani di Sumsel
Meski tidak lagi membersamai Sriwijaya FC, Coach Yoyo tetap mendoakan klub kebanggan wong kito ini agar selalu menang di setiap laga ke depan.
"Do'a yg terbaik untuk Sriwijaya fc di setiap game nya Dan bsok menang insyaAllah. Aamin YRA," pinta Coach Yoyo dalam doanya.