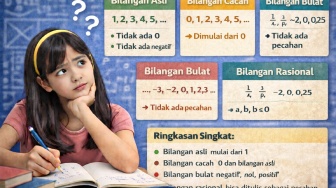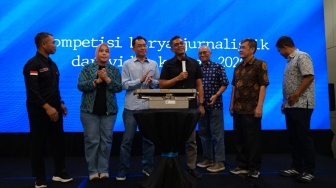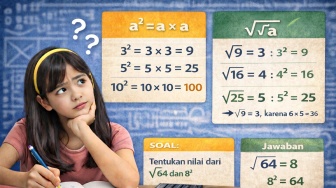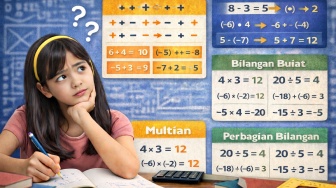SuaraSumsel.id - Di balik lembah dan lekuk bukit barisan yang menghijau di Sumatera Selatan, hidup sebuah kebijaksanaan yang terus mengalir kepada anak-anaknya. Namanya Tunggu Tubang, yakni sebuah sistem adat masyarakat Semende yang tak hanya diwariskan, tetapi juga dijaga sepenuh jiwa.
Eliana, perempuan dari Desa Muara Tenang, Semende Darat Ulu, baru saja menyematkan status baru dalam hidupnya. Anak perempuannya, sang sulung, telah menikah.
Dan itu berarti, Eliana resmi membuka Tunggu Tubang yakni sebuah rumah adat baru, tempat pusaka keluarga berakar dan tumbuh.
“Kami para ibu, berharap anak-anak kami, baik perempuan maupun laki-laki, bisa melanjutkan dan mempertahankan adat Tunggu Tubang ini,” kata Eliana dengan mata berkaca.
Baca Juga:Modus Oknum Bhayangkari di Sumsel Janjikan Lulus Bintara, Ternyata Peras Rp1,6 Miliar
Dalam budaya Semende, Tunggu Tubang bukan sekadar gelar.
Ia adalah benteng adat, pemegang kuasa atas rumah, sawah, dan kebun, pusaka yang tak boleh diperjualbelikan.
Sang pewaris adalah anak perempuan tertua, atau anak laki-laki jika perempuan tak ada.
Namun, bukan berarti mereka yang bukan sulung kehilangan hak menjaga warisan.
“Kami percaya, Tunggu Tubang tak akan pernah tumbang karena anak tengah dan bungsu tetap bisa membuka Tunggu Tubang baru,” ujar Hasan Zen, tokoh adat di desa itu.
Baca Juga:Tips Hadapi Listrik Padam 5 Jam di Sumsel Akhir Pekan Ini, Nomor 4 Jarang Diketahui
Di Semende, adat bukan hanya urusan masa lalu.
Ia adalah masa kini dan masa depan. Ia mengikat tiga kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut dalam sebuah kesatuan wilayah adat seluas hampir 100 ribu hektar.
Di atas tanah itulah berdiri rumah-rumah kayu berusia ratusan tahun, ladang kopi seluas 15.640 hektar, dan sawah-sawah sebagai lumbung pangan keluarga.
Tentu, tak mudah menjaga semua itu dari gempuran zaman.
Tapi adat Tunggu Tubang justru menjadi tameng yang membuat tanah Semende tak terjual, tak tergadai. Ia tumbuh, meluas.
Tak hanya di Muara Enim, tetapi juga sampai ke Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Di sana, keluarga-keluarga Semende membentuk marga-marga baru yakni Muara Saung, Pulau Beringin, Ulu Nasal, Pajarbulan Seginim, hingga Ulak Rengas. Mereka semua tetap menjaga warisan yang sama: tanah, rumah, dan kehormatan.
Tunggu Tubang bukanlah tembok.
Ia adalah pelita. Dari generasi ke generasi, ia membimbing langkah anak cucu untuk tak melupakan dari mana mereka berasal. Dalam diam, dalam adat, Semende tetap berdiri.
Menikah, adalah salah satu syarat orang Semende dianggap sah untuk menyandang status sebagai Tunggu Tubang.
Eliana anak tengah. Awalnya, ia bukanlah Tunggu Tubang, yang mendapatkan pusaka berupa rumah, sawah, dan kebun.
Dalam budaya Suku Semende, anak tertua perempuan atau laki-laki (jika sebuah keluarga .dak memiliki anak perempuan) akan dijadikan Tunggu Tubang. Mereka akan mengelola pusaka berupa rumah, sawah, dan kebun, untuk kepen.ngan keluarga. Pusaka tersebut .dak boleh diperjualbelikan, dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Fungsinya, sebagai kedaulatan pangan dan ekonomi bagi keluarga.
“Kami percaya Tunggu Tubang .dak akan pernah tumbang karena anak tengah dan anak bungsu yang .dak mendapat pusaka keluarga, tetap bisa dan mau membuka Tunggu Tubang baru,” kata Hasan Zen, salah satu tokoh adat di Desa Muara Tenang.
“Semende masih ada juga karena masih bertahannya Tunggu Tubang,” lanjut Hasan Zen.
Saat ini, semua wilayah adat awal Suku Semende dibagi .ga kecamatan; Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut, yang masuk Kabupaten Muara Enim.
Selama ratusan tahun, wilayah adat tersebut tetap bertahan. Tidak terjual atau tergusur oleh kelompok masyarakat lain, termasuk para pelaku usaha. Bahkan, beberapa rumah panggung kayu yang berusia ratusan tahun masih bertahan.
Dengan sistem adat Tunggu Tubang, maka wilayah adat Suku Semende di Muara Enim adalah gabungan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut, seluas 99.802 hektar.
Dari luasan tersebut, sekitar 15.640 hektar merupakan perkebunan kopi, yang menjadi sumber ekonomi utama Suku Semende. Sementara sawah sebagai sumber pangan, luasnya mencapai 3.650 hektar.
Dari tradisi yang dapat melahirkan Tunggu Tubang baru, maka wilayah adat Suku Semende yang semula hanya di lembah perbukitan Gunung Patah di Kabupaten Muara Enim, meluas ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), hingga wilayah Lampung dan Bengkulu.
Di Kabupaten OKUS, Suku Semende mengembangkan Marga Muara Saung dan Marga Pulau Beringin. Di Bengkulu, terdapat Marga Semende Ulu Nasal dan Marga Semende Pajarbulan Seginim. Sementara di Lampung, antara lain Marga Semende Wai Tenung, Marga Semende Wai Sepu.h,
Marga Semende Kasui, Marga Semende Pughung, dan Marga Semende Ulak Rengas. Sama seper. Suku Semende di Kabupaten Muara Enim, mereka yang menyebar tersebut juga menjalankan sistem adat Tunggu Tubang. Puluhan ribu hektar wilayah permukiman, persawahan, dan perkebunan menjadi harta pusaka keluarga, yang .dak dapat diperjualbelikan.
Karena diamanahkan untuk mengelola pusaka keluarga; sawah, rumah, kebun, dan tebat, sosok Tunggu Tubang harus punya banyak pengetahuan serta kearifan untuk memas.kan keberlanjutan pusaka yang dikelolanya bersama dengan keluarga.
“Sebagian besar pengetahuan Tunggu Tubang terkait dengan tata kelola pangan, namun ada banyak Tunggu Tubang juga yang bisa guritan, menari, tadut, kuntau (laki-laki), amanatak, dan kesenian lainnya,” kata Karman, salah satu tokoh masyarakat, serta peneli. adat Semende, kelahiran Desa Pajar Bulan, Semende Darat Ulu.
“Tunggu Tubang bisa dikatakan sebagai lumbung pengetahuan Semende,” lanjut Karman.
Di bidang pangan, kata Karman, seorang Tunggu Tubang memiliki pengetahuan tentang kapan waktu yang tepat untuk menyemai benih, menanam, dan melakukan panen padi. Kalender tanam ini berguna untuk menghindari berbagai jenis hama.
“Waktu menyemai benih padi hingga masa panen, biasanya bertepatan dengan waktu hama berkembang biak, sehingga mereka (hama) .dak menyerang tanaman padi,” lanjut Karman.
“Tunggu Tubang juga paham beragam jenis-jenis padi lokal yang biasanya punya karakter khusus dalam rangka mengatasi perubahan musim, misalnya padi jambat teras yang punya rumpun besar dan lebih tahan terhadap angin kencang di musim-musim tertentu,” lanjutnya.
Sosok Tunggu Tubang juga harus bijak dalam melakukan manajemen air di irigasi sawah mereka. Sepetak sawah harus mendapat cukup air, .dak boleh kurang ataupun lebih. Mereka juga harus cerdas memanfaatkan landskap dangau (kebun) agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka.
“Di dangau, kalau kita lihat, Tunggu Tubang .dak hanya menanam padi, tetapi juga sayuran seper. labu, tanaman obat, memelihara ikan, i.k, kambing, dan lainnya. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan pangan (karbohidrat dan nutrisi) dan kesehatan keluarga,” kata Karman.
Di bidang kuliner, Tunggu Tubang punya pengetahuan mengolah beragam jenis kuliner khas, sepe. serabi, lemang, hingga olahan fermentasi “bekasam” yang bahannya dari ikan dan nasi (padi).
“Jika melihat semua itu, Tunggu Tubang adalah sosok perempuan yang cerdas, bijak dan tangguh. Kita orang Semende, harus bangga dengan Tunggu Tubang,” tegas Karman.
Perkumpulan Pemuda Pelestari Tunggu Tubang
Saat ini, hampir 30 persen dari populasi nasional merupakan Gen-Z (1997-2012). Situasi ini juga mirip seper. di Semende, dimana Gen-Z cukup mendominasi dan berpotensi untuk mempengaruhi kondisi sosial-budaya masyarakat Semende.
“Keberadaan mereka menjadi sangat pen.ng sebagai generasi penerus Tunggu Tubang,” kata Muhammad Tohir, Koordinator Program Ghompok Kolek.f: “Tunggu Tubang Tak Akan Tumbang: Kedaulatan Pangan Berkelanjutan” yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana dan LPDP.
Melihat potensi tersebut, Ghompok Kolek.f berinisia.f untuk membentuk sebuah perkumpulan Pelestari Tunggu Tubang yang berisi 25 pemuda yang berasal dari 11 desa yang tersebar di Kecamatan Semende (Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Laut).
Dari kuesioner yang dilakukan oleh Ghompok Kolek.f, sekitar 60 persen dari mereka merupakan anak tengah, 26 persen adalah Tunggu Tubang, dan 13 persen lainnya adalah calon Tunggu Tubang.
“Kami berharap, baik itu anak tengah, calon Tunggu Tubang, dan semua Gen-Z di Semende dapat bersama-sama mempertahankan dan terus melestarikan Tunggu Tubang,” kata Ahmad Rizki Prabu, salah satu founder Ghompok Kolek.
Erfan Fahliansyah, Ketua Perkumpulan Pelestari Tunggu Tubang mengatakan, sejauh ini, inisiatif pembentukan perkumpulan ini sangat berdampak, terutama kepada generasi muda yang awalnya menganggap Tunggu Tubang sebagai beban.
“Perlahan kami sadar bahwa adat Tunggu Tubang itu memang ditujukan puyang kami dulu untuk kebaikan masyarakat Semende itu sendiri,” kata Erfan.
Ani Widia Sari, Tunggu Tubang di Desa Tanjung Tiga, sekaligus Humas Perkumpulan Pelestari Tunggu Tubang meyakini, masih banyak pengetahuan adat Semende terkait dengan Tunggu Tubang yang dapat digali dan bermanfaat bagi orang banyak.
“Kami mengajak semua kance-kance (teman-teman) di Semende ini untuk dapat bergabung, dan bersama-sama untuk dapat menggali dan melestarikan ragam pengetahuan Tunggu Tubang yang pas. akan sangat berguna bagi masa depan pangan Indonesia, khususnya di Semende,” katanya.